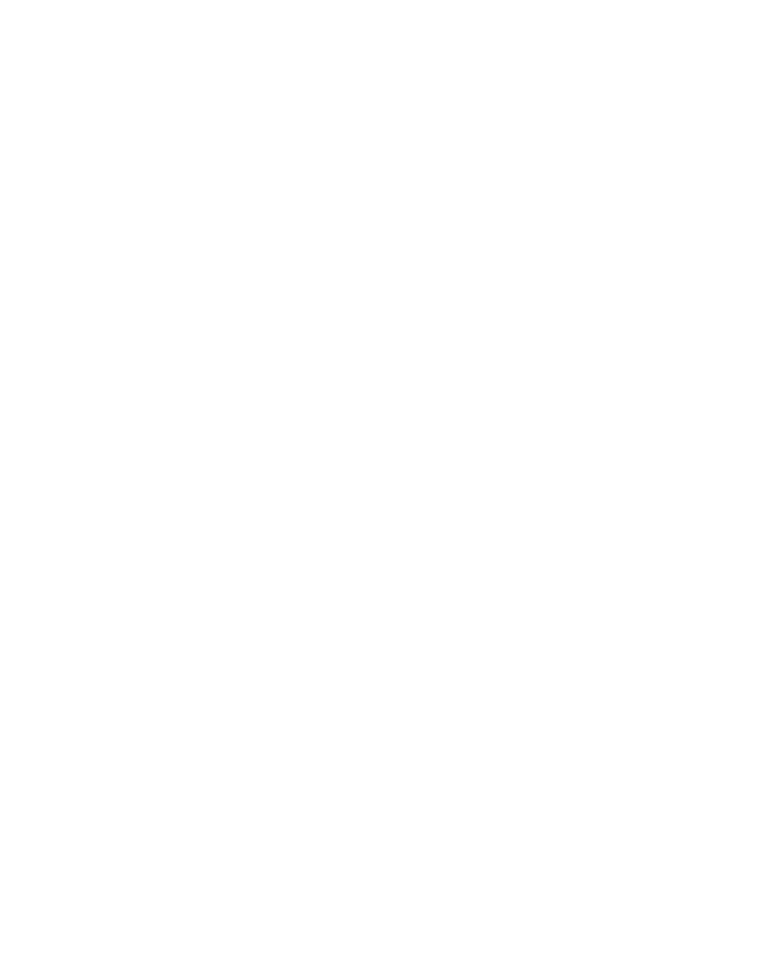Oleh: Imam Mustofa
(Dosen Pascasarjana UIN Jurai Siwo Lampung)
Penghujung tahun 2025 menjadi saksi terjadinya bencana besar yang melanda sebagian wilayah bumi pertiwi. Banjir bandang terjadi di beberapa wilayah. Air bah mengamuk tanpa arah. Hamparan hutan yang berubah menjadi lapang gersang menjadikan air bah leluasa menerjang apa saja yang ia lewati tanpa hambatan. Tanah longsor meluncur tanpa ada yang bisa menghalau. Banjir bandang yang menyayat keindahan wajah ibu pertiwi. Menorehkan luka yang menganga. Menelan korban jiwa dan mengalirkan banyak air mata.
Terjadinya bencana alam tersebut seolah mengguncang kesadaran kolektif masyarakat Indonesia. Bencana tersebut tidak hanya menciptakan ruang saling menyalahkan, akan tetapi juga menjadi trigger introspeksi dan upaya mencari Solusi. Usaha untuk penanganan secara permanen dan dab berkelanjutan. Salah satu istilah yang muncul sebagai upaya mencari solusi bencana alam tersebut adalah Ekoteologi.
Ekoteologi bukanlah konsep atau istilah baru. Istilah yang sebelumnya popular adalah Teo-ekologi, karena ia lebih dulu muncul. Ia diperkenalkan pada awal tahun 1970-an oleh seorang Filosuf Norwegia, Arne Ness (Callenbach, 1993). Seiring dengan perkembangan, istilah Teoekologi berevolusi menjadi istilah yang lebih mapan di dunia akademik pada tahun 1990-an. Terlepas dari perbedaan istilah dalam berbagai agama dan kitab suci, yang jelas, dua istilah tersebut menekankan pada tanggung jawab manusia sebagai makhluk Tuhan terhadap keberlangsungan bumi yang juga ciptaan-Nya yang dianugerahkan kepada manusia.
Disuaraknnya kembali ekoteologi saat terjadi bencana alam stelah seolah “perangkat pengelolaan alam” lainnya sudah tidak berdaya menghadapi perusakan dan kerusakan alam dan lingkungan. Hukum seolah tak berdaya menghadapi eksploitasi alam. Penegakan hukum lingkungan tak lagi mempertimbangkan dan mengedepankan keberlangsungan bumi. Kearifan lokal dalam menyayangi alam seolah tergerus dengan gelombang perkembangan teknologi dengan berbagai fiturnya. Di tengah “frustasi kolektif” inilah, ekoteologi kembali kencang disuarakan.
Ekoteologi: transformasi nilai ketuhanan yang ramah lingkungan
Tujuan manusia beragama nampaknya sudah mengalami pergeseran. Hal ini diungkapkan secara Kritis oleh Ilmuan Muslim asal Iran, Abdul Karim Soroush. Menurutnya, paradigma masyarakat beragama saat berbeda dengan masyarakat masa lalu. Dulu agama dipandang dengan perspektif kewajiban. Sementara saat ini beragama dipandang sebagai hak. Hal ini mempunyai konsekuensi yang sangat serius terhadap cara sesorang memperlakukan ajaran agama.
Ketika beragama dimaknai sebagai kewajiban, maka pemeluknya secara terikat melaksanakan ajarannya. Sementara saat agama dipandang sebagai hak, maka menjalankan ajaran dan tuntunannnya dipandang sebagai pilihan. Lalu apa konsekuensinya terhadap sikap kepada lingkungan dan alam?
Paradigma beragama sebagai hak tidak jauh berbeda dengan menjadikan agama sebagai identitas sosial formal semata. Agama bahkan menjadi jubah untuk menutupi kebobrokan moral. Agama seolah menjadi topeng untuk melakukan hal-hal yang kontradiktif dengan esensi ajaran agama. Menjadikan agama sebagai tameng untuk menutupi tindakan destruktif yang bertentangan dengan nilai-nilai agama dan ketuhanan. Agama malah bisa menjadi justifikasi perusakan lingkungan dan alam dengan paradigma ini. Karena dengan paradigma ini, menggunakan ajaran dan nilai agama atau tidak, hanya sebagai pilihan.
Konsep ekoteologi tidak sebatas konteks beragama, akan tetapi lebih dari itu, yaitu bertuhan. Manusia bisa saja beraga secara formal, namun pada tataran “bertuhan”, dalam kesadaran mereka akan mengakui keberadaan Tuhan secara substantif. Mengakui dan mentaati aturan dan melaksanakan nilai-nilai ketuhanan. Menjadikan Tuhan sebagai pusat dari alam semesta. Inilah paradigma teosentris. Masalahnya, apakah paradigma ini terefleksi dalam perilaku manusia terhadap alam? Apakah paradigma teosentris ini mampu mengantarkan manusia pada kesadaran penuh untuk menjaga alam dan melestarikannya? Mengingat alam semesta adalah anugerah dari Tuhan. Bahkan keindahan alam semesta tersebut sebagai refleksi Tuhan itu sendiri. Jawabannya cenderung tidak.
Paradigma Teosentris perlu direfeleksikan dalam bentuk konstruktif untuk menjaga relasi manusia dengan alam. Tuhan sebagai pusat nilai, namun nilai-nilai itu perlu direfleksikan dalam berperiku. Manusia harus memperlakukan alam semesta dengan baik. Memosisikan diri mereka sebagai wakil Tuhan di muka bumi (khalifatullah fil ardh). Menjadi wakil tuhan untuk menjaga keindahan dan keberlangsungan alam semesta. Menjadi wakil tuhan untuk memproyeksikan nilai-nilai keindahan Tuhan dalam bentuk perilaku kepada siapa pun dan apa pun.
Ekoteologi tidak dimaknai hanya menghadirkan Tuhan dalam eksistensi alam semesta. Ekoteologi dimaknai dengan paradigma ekosentris. Paradigma yang memandang dan memosisikan alam semesta dan seluruh ekosistem sebagai kesatuan yang utuh, terintegrasi denga erat serta memiliki eksistensi dan nilai yang sama. Dengan paradigma ini maka manusia beragama dan bertuhan akan memandang manusia adalag bagain integral dari alam. Mereka akan menjaga keseimbangan alam semesta.
Paradigma ekosentris akan menuntun manusia untuk tidak akan merasa superior atas makhluk lain, terutama alam. Mereka akan menjaga relasi yang harmonis dengan lingkungan dan alam semesta. Manusia akan bertindak bukan hanya untuk memenuhi egonya. Menusia tidak hanya berusaha menjaga keberlangsungan kehidupan mereka, akan tetapi juga menjaga keberlangsungan makhluk hidup lainnya dan alam semesta.[]