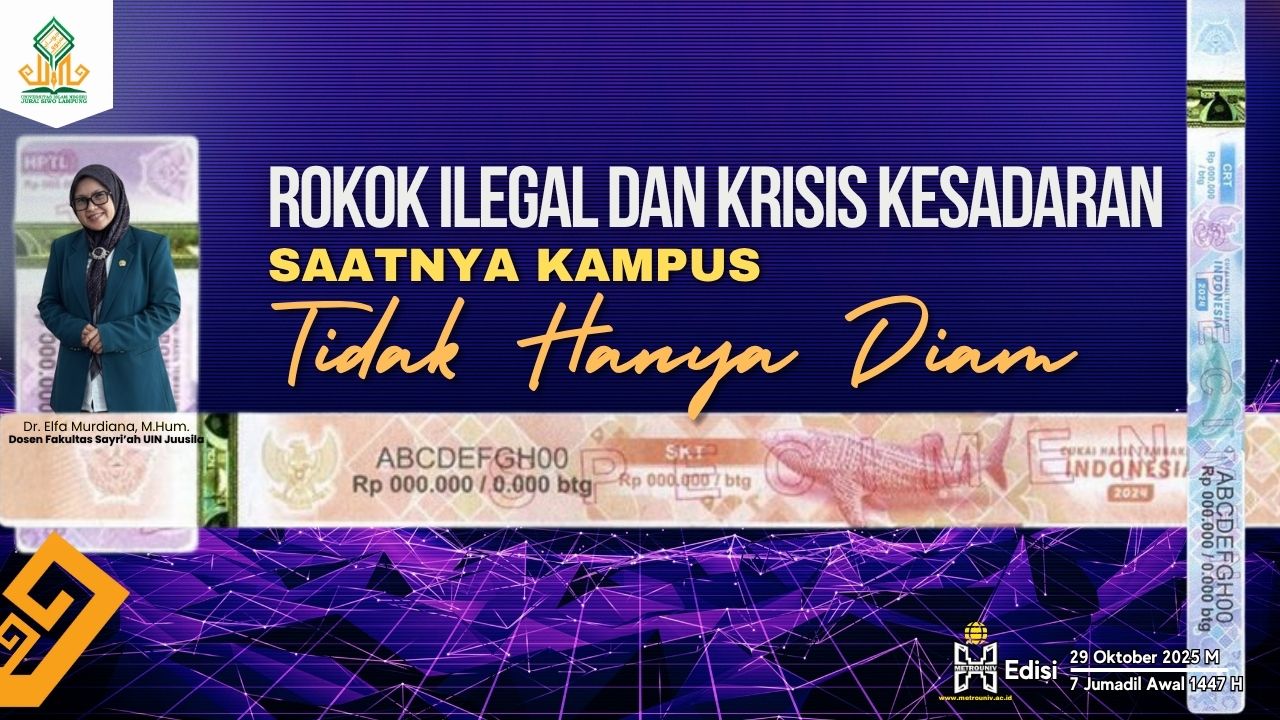metrouniv.ac.id – 29/10/2025 – 7 Jumadil Awal 1447 H
Dr. Elfa Murdiana, M.Hum. (Dosen Fakultas Syari’ah UIN Jurai Siwo Lampung)
Harga rokok yang terus meningkat akibat kebijakan kenaikan cukai telah menimbulkan paradoks sosial yang kian nyata. Di satu sisi, kebijakan tersebut dimaksudkan untuk menekan konsumsi dan meningkatkan pendapatan negara, namun di sisi lain justru melahirkan pasar alternatif karna peredaran rokok ilegal menawarkan pasar dengan harga jauh lebih murah. Bagi sebagian masyarakat, pilihan ekonomi menjadi lebih dominan dibanding kesadaran hukum. Mereka membeli rokok tanpa memedulikan legalitasnya, selama harganya terjangkau. Fenomena ini menjalar cepat di berbagai lapisan sosial, dari pekerja dewasa hingga remaja, bahkan pelajar dan mahasiswa menjadikan rokok ilegal semakin mudah diterima dan dinormalisasi dalam kehidupan sehari-hari. Akibatnya, pasar gelap rokok tidak hanya bertahan, tetapi juga tumbuh subur sebagai respons atas kebijakan fiskal yang belum sepenuhnya memperhitungkan realitas sosial di tingkat konsumen.
Lampung di Persimpangan Asap Gelap Rokok Illegal
Lampung kini menempati posisi strategis dalam rantai distribusi rokok ilegal di Indonesia. Sebagai penghubung antara Jawa dan Sumatra, provinsi ini menjadi jalur favorit penyelundupan produk tanpa pita cukai. Data Bea Cukai Bandar Lampung menunjukkan, pada pertengahan 2024 saja lebih dari 3,1 juta batang rokok ilegal berhasil diamankan, sementara tahun sebelumnya 40 juta batang dimusnahkan hasil penindakan 2023-2024. Fakta ini mengindikasikan bukan hanya maraknya aktivitas kriminal, tetapi juga kegagalan sistemik dalam pengawasan dan penegakan hukum yang berkelanjutan.
Sebagian besar rokok ilegal yang beredar di Lampung ternyata bukan diproduksi di sana, melainkan dikirim dari pusat-pusat produksi di Pulau Jawa terutama Jawa Tengah dan Jawa Timur sehingga peran Lampung lebih sebagai jalur distribusi ketimbang pusat produksi. Data penindakan Bea Cukai Bandar Lampung menunjukkan bahwa dalam operasi pertengahan 2024 saja telah diamankan lebih dari 3,1 juta batang rokok ilegal. Laporan-laporan investigasi media dan pemerintah daerah menguatkan bahwa Jawa Tengah dan Jawa Timur merupakan wilayah dengan aktivitas produksi rokok ilegal yang signifikan. Rute distribusi pun sering mengalir dari dua wilayah tersebut menuju Sumatra melalui jalur transit utama.
Modus operandi para pelaku juga semakin variatif dan tersinkronisasi dengan jaringan logistik modern: rokok disamarkan di belakang tumpukan barang dalam truk, dikirim melalui jasa ekspedisi daring, dan titik-transit seperti Pelabuhan Bakauheni dimanfaatkan secara sistematis sebagai pintu masuk ke Pulau Sumatra. Fenomena ini memperlihatkan bahwa ekonomi ilegal rokok telah bertransformasi dari produksi rumahan tersebar menjadi jejaring distribusi terorganisir yang memadukan sentra produksi di Jawa dengan sistem logistik modern untuk menjangkau pasar luas di luar Jawa.
Kritik atas Penegakan Hukum Pidana Rokok Ilegal: Antara Simbol dan Substansi
Negara melalui kebijakan cukai berupaya menekan konsumsi rokok dan menjaga stabilitas penerimaan fiskal. Namun di lapangan, kebijakan tersebut justru sering menimbulkan efek paradoksal: semakin tinggi cukai, semakin subur pasar ilegal. Ketika rokok legal menjadi terlalu mahal, konsumen terutama dari kelompok berpenghasilan rendah dan mahasiswa beralih pada produk tanpa pita cukai yang dijual bebas dan murah.
Secara normatif, pelanggaran terhadap ketentuan cukai rokok diatur dalam Pasal 54 hingga 56 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai. Pasal-pasal tersebut secara tegas memuat sanksi pidana penjara hingga lima tahun dan denda maksimum sepuluh kali nilai cukai. Namun dalam praktiknya, penegakan hukum terhadap pelaku peredaran rokok ilegal sering kali berhenti pada penyelesaian administratif melalui denda. Pola ini bukan semata soal efektivitas penindakan, tetapi memperlihatkan kecenderungan reduksi makna hukum pidana menjadi sekadar formalitas penertiban ekonomi, bukan instrumen moral dan sosial yang mendidik masyarakat.
Dari perspektif hukum pidana materiil, tindakan memproduksi, mengangkut, atau memperjualbelikan rokok tanpa pita cukai jelas memenuhi unsur actus reus yakni perbuatan melawan hukum yang nyata. Sementara itu, kesadaran dan kehendak pelaku untuk mendapatkan keuntungan ekonomi melalui cara-cara ilegal menegaskan adanya mens rea, atau unsur kesalahan berupa niat jahat (intentional wrongdoing). Dengan demikian, peredaran rokok ilegal bukanlah pelanggaran administratif ringan, melainkan tindak pidana ekonomi yang memiliki dampak fiskal dan sosial luas terhadap negara dan masyarakat.
Sayangnya, dalam implementasi, pendekatan hukum sering kali berhenti pada prinsip ultimum remedium yakni hukum pidana sebagai upaya terakhir tanpa mempertimbangkan konteks sosial dan kerugian negara yang besar. Prinsip ini kerap dimaknai secara keliru sebagai bentuk kelonggaran bagi pelaku, bukan sebagai alat untuk menegakkan keadilan proporsional. Akibatnya, efek jera tidak tercapai, dan pasar rokok ilegal terus bertumbuh karena biaya pelanggaran dianggap lebih ringan daripada risiko hukumnya.
Lebih jauh, jika ditinjau dari perspektif fungsi preventif dan pedagogis hukum pidana, maka sanksi yang terlalu lunak justru menimbulkan anomali hukum. Hukuman administratif semata gagal menanamkan pesan moral bahwa pelanggaran terhadap rezim cukai adalah bentuk penipuan terhadap negara dan masyarakat. Oleh karena itu, reformasi penegakan hukum pidana cukai perlu menekankan tiga hal: pertama, memperjelas pembedaan antara pelanggaran administratif dan tindak pidana murni; kedua, memperkuat pembuktian unsur kesalahan (mens rea) agar pelaku utama dapat dijerat secara tepat; dan ketiga, menata ulang sanksi agar tidak hanya bersifat represif, tetapi juga edukatif dan rekonstruktif, misalnya melalui kerja sosial, pembinaan usaha legal, atau restitusi pajak bagi pelaku ekonomi kecil yang terdorong oleh ketimpangan harga cukai.
Tanpa keberanian menegakkan hukum secara substantif, bukan hanya formal, negara berisiko kehilangan kewibawaannya di mata publik. Hukum pidana akan tetap menjadi “simbol ketegasan tanpa keberanian,” sementara pasar gelap terus bekerja dengan logika efisiensi dan keuntungan yang jauh lebih rasional dibanding logika keadilan negara.
Perguruan Tinggi: Dari Menara Gading ke Garda Etik
Dimensi sosial yang tak kalah penting ialah munculnya mahasiswa sebagai konsumen baru rokok ilegal. Harga rokok legal yang melonjak membuat sebagian mahasiswa beralih pada produk murah tanpa pita cukai. Fenomena ini menandakan adanya crisis of awareness di kalangan terdidik: kelompok yang diharapkan menjadi motor rasionalitas justru turut memperkuat rantai ekonomi gelap. Di sinilah muncul ironi moral, jika kampus gagal menanamkan kesadaran hukum dan etika sosial, maka pendidikan tinggi kehilangan maknanya sebagai ruang pembentukan karakter warga negara. Melawan rokok ilegal bukan hanya urusan fiskal dan pidana, tetapi juga tanggung jawab moral untuk menolak normalisasi pelanggaran hukum dalam kehidupan sehari-hari.
Kampus tidak boleh hanya menjadi pengamat. Ia harus turun tangan bukan dengan retorika, melainkan dengan gerakan intelektual yang konkret. Ada tiga langkah strategis yang dapat diambil:
- Membangun riset kebijakan dan advokasi publik tentang efektivitas cukai, perilaku konsumsi muda, dan dampak sosial ekonomi peredaran ilegal.
- Mendorong literasi hukum dan ekonomi etis di lingkungan kampus, agar mahasiswa memahami implikasi moral dari pilihan konsumsi mereka.
- Berjejaring dengan Bea Cukai, pemerintah daerah, dan media kampus untuk membangun sistem edukasi publik dan pengawasan sosial yang berkelanjutan.
- Peredaran rokok ilegal adalah potret kecil dari kontradiksi besar bangsa ini: ketika hukum ditegakkan tanpa kesadaran, dan pendidikan berjalan tanpa moralitas.
Rokok ilegal bukan sekadar barang murah; ia adalah simbol dari lemahnya kesadaran hukum dan etika sosial kita bersama. Sudah saatnya negara dan perguruan tinggi berjalan seirama dalam menegakkan moralitas publik. Negara memperkuat hukum dan pengawasan, sementara kampus menumbuhkan kesadaran hukum serta tanggung jawab sosial generasi muda.
Selama kampus hanya diam, ruang pendidikan justru ikut membiarkan generasi muda menjadi bagian dari masalah, bukan solusi. Perguruan tinggi harus kembali pada perannya sebagai penjaga moralitas publik dengan mendidik bukan hanya untuk bekerja, tetapi juga untuk taat pada nilai dan hukum. Sebab tanpa kesadaran yang lahir dari pengetahuan, penegakan hukum hanyalah ritual, bukan pembebasan. Dan sebagaimana negara gagal tanpa warganya yang sadar hukum, pendidikan pun kehilangan makna tanpa kesadaran moral di baliknya.